Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024, dan hasilnya mengejutkan banyak pihak: indeks integritas sektor pendidikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah berbagai upaya reformasi, anggaran yang terus digelontorkan, dan gembar-gembor tentang pentingnya karakter, hasil ini menyisakan pertanyaan serius: mengapa integritas justru kian terkikis di dunia pendidikan kita?
Dalam banyak narasi pembangunan nasional, pendidikan selalu disebut sebagai pondasi utama pembentukan manusia unggul. Namun, jika integritas sebagai pilar moral justru merosot, maka rasanya yang dibangun bukanlah generasi berkarakter, melainkan generasi yang cerdik mencari celah, lihai berdusta, dan nyaman berada dalam ketidakbenaran. Mengapa ini bisa terjadi?
Survei SPI Pendidikan KPK menilai tingkat integritas berdasarkan persepsi siswa, guru, kepala sekolah, hingga orang tua terhadap praktik korupsi dan kecurangan di lingkungan pendidikan. Penilaian mencakup indikator seperti pungutan liar, manipulasi nilai, kecurangan ujian, jual beli jabatan di institusi pendidikan ketidakdisiplinan, akademik gratifikasi, hingga ketidakadilan dalam pemberian beasiswa.
Penurunan nilai integritas ini bukan sekadar persoalan teknis atau administratif. Ia menunjukkan sebuah krisis nilai yang lebih dalam, di mana kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral telah lama berada dalam posisi terpinggirkan — baik oleh sistem maupun budaya yang dibentuk bertahun-tahun.
Kita sering mengira bahwa integritas adalah sesuatu yang personal. Tapi dalam konteks pendidikan, integritas harus menjadi nilai yang diinstitusikan — dibentuk, didukung, dan dipelihara oleh sistem. Namun bagaimana mungkin itu terjadi jika justru sistem pendidikan kita sendiri membuka celah bagi perilaku tidak etis?
Menjadi individu yang berintegritas di sistem yang tidak mendukung integritas adalah perjuangan sunyi. Banyak guru yang memilih diam karena takut dipindahkan atau tidak diperpanjang kontraknya. Banyak siswa yang memilih ikut menyontek karena tidak ingin dikucilkan. Banyak kepala sekolah yang terjebak praktik manipulatif karena tekanan dari atas dan harapan dari bawah.
Perspektif Psikologi Sosial: Mengapa Sulit Menjaga Integritas?
Dalam psikologi sosial, ada banyak pemikiran tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan budaya yang membentuk mereka. Salah satu tokoh penting, Philip Zimbardo, melalui eksperimennya yang terkenal Stanford Prison Experiment, menunjukkan bahwa perilaku individu bisa sangat mudah dipengaruhi oleh peran sosial dan norma lingkungan. Zimbardo menyimpulkan bahwa “situasi sering kali lebih kuat daripada karakter pribadi.” Ini berarti, bahkan individu yang pada dasarnya berintegritas tinggi pun bisa tergelincir dalam ketidakjujuran jika berada di sistem yang membenarkan perilaku tersebut.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, budaya yang membiarkan kecurangan menjadi “normal” menciptakan situasi yang sangat kuat, sehingga mempersulit individu mempertahankan integritas pribadi. Saat menyontek dianggap lumrah, saat pungutan liar dilihat sebagai “biaya biasa,” maka tekanan sosial untuk beradaptasi jauh lebih besar daripada keberanian untuk melawan.
Albert Bandura, melalui konsep moral disengagement, juga memberikan pencerahan tentang fenomena ini. Ia menjelaskan bahwa individu bisa merasionalisasi tindakan tidak bermoral mereka melalui mekanisme psikologis seperti pembenaran moral (semua orang juga melakukannya), pengalihan tanggung jawab (ini perintah atasan), atau dehumanisasi korban (ini hanya sistem, bukan menyakiti orang). Dalam budaya pendidikan kita, pembenaran-pembenaran ini sering digunakan untuk menenangkan rasa bersalah ketika melakukan pelanggaran integritas.
Di sisi lain, Erich Fromm dalam Escape from Freedom mengungkapkan bahwa banyak orang lebih nyaman menyerahkan otonomi moral mereka kepada otoritas atau norma kelompok daripada menghadapi beban tanggung jawab sendiri. Artinya, banyak guru, siswa, bahkan kepala sekolah tahu bahwa tindakan mereka salah, tetapi merasa lebih aman “ikut arus” daripada berdiri sendiri melawan budaya yang sudah mengakar.
Kurt Lewin, pelopor teori medan (field theory), mempertegas bahwa perilaku individu adalah hasil interaksi dinamis antara orang dan lingkungannya (B = f(P,E), Behavior = function of Person and Environment). Dalam lingkungan pendidikan yang penuh kompromi, tekanan kolektif dari lingkungan itu membentuk perilaku individu lebih kuat daripada nilai-nilai pribadi yang dipegangnya. Maka, tanpa perubahan lingkungan sekolah secara menyeluruh, usaha individu untuk menjaga integritas hampir selalu berakhir dengan isolasi atau kegagalan.
Dari sisi sosiologi, Émile Durkheim, bapak sosiologi modern, menekankan pentingnya norma sosial dalam membentuk kesadaran kolektif (collective consciousness). Menurut Durkheim, norma sosial yang mengakar kuat akan menentukan mana yang dianggap “biasa” dan “aneh”. Ketika norma sosial dalam pendidikan menganggap kecurangan, nepotisme, atau manipulasi sebagai hal biasa, maka tindakan integritas tidak hanya sulit diterima, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari harmoni sosial.
Pandangan para tokoh ini memperjelas bahwa menjaga integritas bukan sekadar soal niat baik individual, tetapi tentang perjuangan melawan kekuatan situasional dan budaya kolektif yang sangat kuat. Kesadaran ini penting untuk memahami bahwa perubahan integritas dalam pendidikan membutuhkan transformasi sistemik dan kultural, bukan hanya kampanye etika yang bersifat permukaan.
Menurunnya integritas dalam dunia pendidikan bukanlah sekadar angka dalam laporan survei. Ia adalah cerminan dari tarik-menarik antara nilai yang ingin kita bangun dengan budaya yang sudah terlanjur mendarah daging. Membangun integritas tidak cukup hanya dengan mengajarkan kejujuran di ruang kelas atau menggelar seminar etika sesekali; ia menuntut perubahan kultur, perubahan sistem, dan keberanian untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan-pilihan moral. Seperti yang diajarkan para ahli psikologi sosial dan sosiologi, perubahan perilaku manusia tidak lahir dari ceramah, melainkan dari perubahan medan sosial tempat mereka hidup. Pendidikan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar slogan “integritas”; ia membutuhkan revolusi diam-diam dalam norma, kebiasaan, dan ekosistemnya. Hanya dengan itulah, integritas bisa kembali menjadi nadi utama dalam dunia pendidikan kita — bukan sekadar harapan kosong di atas kertas.




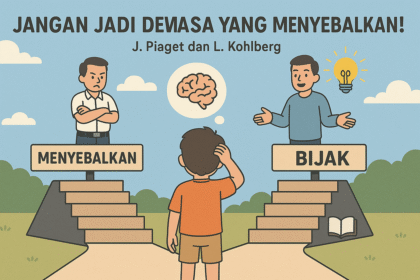

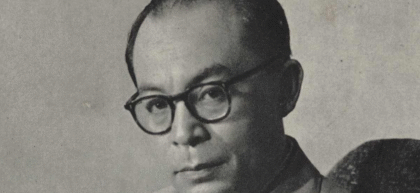



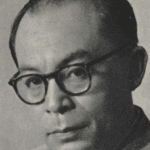


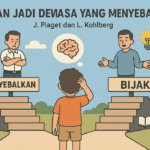
Komentar