Pernahkah kita benar-benar memilih jalan hidup kita sendiri, ataukah selama ini kita hanya mengikuti arus yang terlihat paling mudah dan paling populer? Di tengah dunia yang serba cepat, penuh informasi, dan dibanjiri saran dari “influencer”, banyak dari kita, terutama generasi muda, terjebak dalam ilusi kebebasan. Kita merasa bebas karena bisa memilih konten yang kita tonton, opini yang kita ikuti, bahkan gaya hidup yang kita jalani. Tapi di balik semua itu, mungkin kita sedang menjalani apa yang Erich Fromm sebut sebagai “pelarian dari kebebasan” — menyerahkan keputusan penting hidup kita pada otoritas tak kasat mata: algoritma.
Erich Fromm dalam karyanya Escape from Freedom menulis bahwa banyak orang tidak tahan dengan beban kebebasan yang sejati. Mereka lebih memilih berada dalam kendali otoritas karena takut menanggung konsekuensi dari pilihan sendiri. Dalam konteks hari ini, otoritas itu bukan lagi raja, negara, atau agama dalam bentuk klasiknya — melainkan mesin algoritma yang tahu apa yang kita suka, apa yang harus kita beli, bahkan siapa yang layak kita kagumi. Generasi Z, yang lahir dalam dekapan teknologi, menjadi generasi paling “bebas” dalam sejarah, namun juga generasi yang dirasa paling kehilangan arah, paling cemas, dan paling bingung membedakan antara pilihan otentik dan hasil manipulasi digital.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada krisis identitas dan ketidakmampuan mengambil tanggung jawab eksistensial. Banyak anak muda merasa “tak punya arah,” bukan karena tak ada pilihan, melainkan karena terlalu banyak pilihan yang membingungkan. Akibatnya, mereka cenderung mengikuti opini mayoritas, tren viral, dan narasi-narasi yang sudah difilter sedemikian rupa oleh media sosial. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama: benarkah kita merdeka dalam membuat pilihan, atau kita hanya merasa nyaman ketika dipandu oleh suara-suara yang lebih keras dari diri kita sendiri?
Kepribadian yang samar
Dalam psikologi sosial, manusia memang cenderung mencari arah dari “otoritas”. Stanley Milgram menunjukkan bagaimana orang biasa bisa melakukan tindakan ekstrem hanya karena diperintah oleh figur yang tampak berwenang. Milgram menyebut ini sebagai agentic state — di mana seseorang tidak lagi merasa bertanggung jawab atas tindakannya karena ia hanya menjalankan perintah. Jika dulu perintah itu datang dari manusia, kini kita diam-diam tunduk pada sistem otomatis yang mengarahkan perilaku kita lewat preferensi yang tidak kita sadari sedang dibentuk.
Algoritma media sosial dirancang untuk memperpanjang waktu kita berada dalam platform — dengan memberi kita konten yang “kita suka”. Tapi apa yang kita suka belum tentu apa yang kita butuhkan. Inilah jebakan besar generasi Z hari ini: mereka merasa mengenal diri karena semua hal tampak dikurasi berdasarkan “minat mereka,” padahal minat itu sendiri adalah hasil dari eksposur berulang. Dalam waktu singkat, mereka bisa merasa bahwa hidup minimalis adalah tujuan hidup, lalu besoknya terobsesi dengan gaya hidup hustle culture, lalu tiba-tiba ingin jadi digital nomad di Bali. Bukan karena kesadaran, tetapi karena ketularan arus.
Zygmunt Bauman menyebut ini sebagai “liquid identity” atau “kepribadian cair” — identitas yang tidak pernah stabil karena terus-menerus terpapar arus perubahan yang tak pernah berhenti. Ketika segala sesuatu bersifat sementara dan bisa diganti dengan satu klik, maka kemampuan untuk membuat keputusan jangka panjang, penuh tanggung jawab, dan mendalam menjadi semakin langka. Akibatnya, generasi muda semakin merasa asing dengan dirinya sendiri. Mereka berputar-putar mencari jati diri, tapi terus berada dalam labirin yang dibentuk oleh algoritma dan ekspektasi sosial.
Kebebasan yang Membangun, Bukan Menghancurkan
Ketika Erich Fromm berbicara tentang “pelarian dari kebebasan,” dia tidak bermaksud mengkritik manusia yang memilih untuk hidup dengan aturan, atau mengandalkan otoritas dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, Fromm memperingatkan kita akan bahaya ketika kebebasan itu menjadi ancaman. Dalam dunia yang serba terhubung, kebebasan sering kali terasa lebih seperti beban, ketimbang anugerah. Banyak di antara kita, termasuk generasi Z, merasa lebih nyaman mengikuti arus informasi yang sudah dikurasi oleh algoritma daripada harus membuat keputusan sendiri. Di sini, kita tidak sedang berbicara tentang kebebasan yang bersifat destruktif atau pemenuhan hasrat sesaat. Kebebasan yang sejati, menurut Fromm, adalah kebebasan yang datang dengan tanggung jawab, yang memberi kita kontrol penuh atas pilihan kita, tanpa menyerahkan hidup kita pada pihak lain.
Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan ini tidak selalu datang secara alami, terutama di tengah lingkungan yang sangat dinamis dan penuh tekanan seperti yang dialami oleh generasi Z saat ini. Mereka tidak hanya menghadapi tuntutan akademik dan sosial, tetapi juga dilema eksistensial yang sering kali dihadapi oleh individu dalam era globalisasi digital. Dalam banyak hal, generasi ini bertumbuh di tengah kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh opini publik — terutama melalui media sosial yang terus-menerus memberi mereka “pilihan-pilihan” yang sudah diatur oleh algoritma. Algoritma ini bukan sekadar memberi mereka konten sesuai minat, tapi juga menciptakan ilusi pilihan. Padahal, pilihan sejati adalah ketika kita bisa mempertimbangkan konsekuensinya, memahami apa yang kita inginkan, dan memilih dengan kesadaran penuh. Bukan hanya memilih apa yang diberikan, apalagi hanya berdasarkan apa yang populer.
Jika kita menilik lebih dalam pada konteks sosial, generasi Z sering dihadapkan pada kontradiksi besar. Di satu sisi, mereka diberi kebebasan untuk berekspresi dan memilih jalur hidup mereka sendiri — dalam pendidikan, karier, atau bahkan dalam kehidupan pribadi. Di sisi lain, mereka terpapar pada tantangan besar yang datang dengan kebebasan itu: ekspektasi sosial, tekanan lingkungan, dan kenyataan pahit bahwa kebebasan juga mengandung tanggung jawab besar. Ketika kebebasan itu terasa menakutkan, maka tidak jarang mereka akan memilih untuk menyerahkannya pada pihak lain, entah itu keluarga, teman, atau bahkan algoritma media sosial yang terus-menerus memberi mereka arahan.
Menemukan Makna di Tengah Kebingungan
Dalam menghadapi kebingungan dan keresahan yang muncul karena kebebasan yang tak terarah, mungkin hal yang paling penting adalah menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Jung, “Manusia yang hanya hidup dalam kebebasan tanpa panduan akan terjebak dalam keputusasaan.” Maka, dalam menghadapi kebingungan ini, bukan berarti kita harus menyerahkan kebebasan kita pada otoritas, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menemukan makna dalam setiap pilihan yang kita buat. Kebebasan bukan tentang memilih tanpa beban, tetapi tentang memilih dengan pemahaman akan konsekuensi yang ditanggung.
Salah satu cara untuk mengatasi kebingungan ini adalah dengan melibatkan diri dalam refleksi diri yang mendalam, serta membangun sistem nilai yang kokoh. Kita perlu bertanya pada diri sendiri: Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat kita merasa puas dan utuh, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang? Dalam konteks generasi Z, ini berarti mulai memfilter informasi yang kita konsumsi, bukan berdasarkan apa yang populer atau mudah dijangkau, tetapi berdasarkan apa yang sejati dan bernilai bagi perkembangan pribadi kita.
Dan ini adalah bagian yang seringkali terlupakan dalam diskusi tentang kebebasan: pentingnya pembelajaran dan pengembangan diri dalam menghadapi kebingungan eksistensial. Generasi Z bukan hanya menghadapi kebingungan karena dunia digital yang penuh dengan informasi yang mengaburkan, tetapi juga karena mereka tidak selalu dilatih untuk berpikir kritis dalam memilih arah hidup. Pendidikan, baik formal maupun informal, memiliki peran yang sangat besar dalam membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih sadar dan bijaksana.
Membangun Otonomi: Jalan yang Tak Populer Tapi Penting
Kebebasan yang sejati bukan soal punya banyak pilihan, tetapi soal kesanggupan menanggung hasil dari keputusan yang kita ambil. Dari sini, kita mulai memahami mengapa banyak anak muda lebih suka jadi “pengikut” — karena menjadi pemimpin atas hidup sendiri menuntut keberanian untuk gagal, kecewa, bahkan kesepian. Tapi justru dalam ruang-ruang sunyi itulah karakter terbentuk. Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensial, berkata, “Kebebasan adalah sisi satu dari mata uang, sisi lainnya adalah tanggung jawab.” Tanpa tanggung jawab, kebebasan hanyalah bentuk lain dari pelarian.
Langkah pertama untuk lepas dari dominasi algoritma adalah dengan menyadari bahwa kita sedang dikendalikan. Membatasi konsumsi media sosial, melatih mindfulness, dan memperdalam refleksi diri menjadi upaya-upaya penting untuk membangun otonomi. Tidak ada algoritma yang lebih canggih dari hati nurani yang jernih. Maka, daripada sibuk mencari apa yang viral, mungkin kita perlu bertanya kembali: apa yang sungguh-sungguh penting bagi hidup kita?
Generasi Z sebenarnya punya kekuatan besar: literasi tinggi, keterhubungan global, dan keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan. Tapi semua itu akan sia-sia jika mereka tidak membangun pondasi eksistensial yang kokoh. Di tengah dunia yang membingungkan, kembalilah pada kesadaran diri. Jangan larikan kebebasanmu kepada algoritma, influencer, atau tren. Ambillah kendali, meski berat. Sebab menjadi manusia bukan soal menjadi benar terus, tetapi tentang kesediaan untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat, dengan sadar dan utuh.


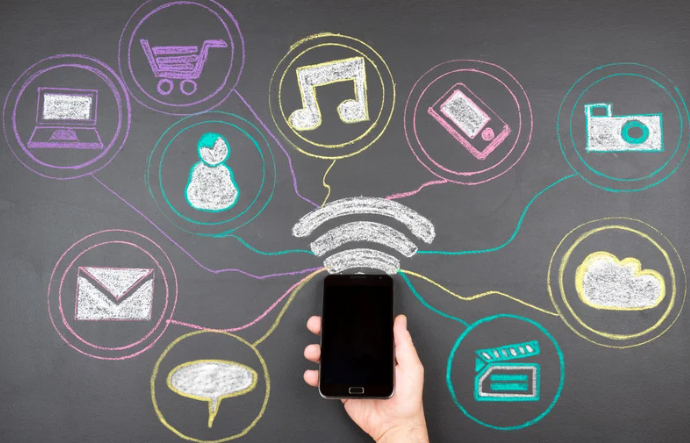


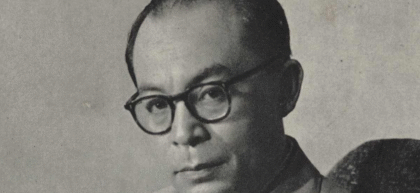



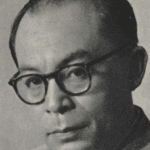


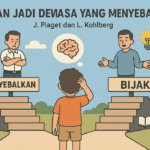
Komentar