
(Ketika intelektual lahir dari tas sekolah, sajadah surau, dan dinginnya Eropa)
Kalau saja Bung Hatta hidup di era sekarang, mungkin orang bakal bilang dia “anak multi-talenta, akademis, religious, dan global-minded”. Tapi karena beliau lahir lebih dari seabad lalu, kita cukup menyebutnya begini: cerdas, saleh, dan berprinsip keras kepala macam batu kali yang tak bisa dibelokkan arus zaman.
Tapi Bung Hatta tidak tiba-tiba jadi Bung Hatta. Ia dibentuk oleh tiga ruang belajar yang sangat khas, dan sangat Indonesia: sekolah kolonial yang mendidik dengan disiplin dan logika Barat, surau Minang yang mengajarkan adab dan akhlak Islam, serta universitas Rotterdam yang menyodorkan pemikiran-pemikiran tajam dari para filsuf dan ekonom dunia. Tiga tempat ini bukan sekadar lokasi, tapi madrasah kehidupan. Di sinilah Bung Hatta dibentuk: bukan cuma sebagai manusia, tapi sebagai gagasan yang hidup.
Bung Hatta kecil disekolahkan di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar khusus anak-anak Belanda dan pribumi elite. Ya, elite. Karena hanya anak pegawai tinggi, bangsawan lokal, atau yang punya koneksi bisa masuk ke situ. Dan, Bung Hatta bukan orang sembarangan. Kakeknya ulama, ibunya pebisnis ulung. Jadi meski ayahnya wafat saat ia bayi, ia tumbuh dalam rumah tangga yang tegak berdiri di atas kaki sendiri.
Di ELS, Hatta belajar membaca dan menulis dalam bahasa Belanda sejak usia dini. Tapi jangan salah kira. Ini bukan tempat belajar yang nyaman kayak TK kekinian. Disiplin kolonial itu keras, kadang kejam. Tapi Hatta muda tidak ciut. Justru di sanalah ia pertama kali membangun hubungan intens dengan buku, dengan logika, dengan dunia yang lebih luas dari Bukittinggi.
Setelah ELS, Hatta lanjut ke MULO (setara SMP) dan AMS (setara SMA) di Padang dan Batavia. Di sinilah bakat intelektualnya makin kelihatan. Ia rajin, teratur, dan… pendiam. Tidak banyak omong, tapi kalau ditanya soal politik dan ekonomi, jawabannya lebih menusuk dari kritik DPR zaman sekarang.
Yang menarik, meski ia dididik dalam sistem pendidikan kolonial, Bung Hatta tidak tumbuh jadi jongos Belanda. Ia belajar dari mereka, tapi tak pernah tunduk pada mereka. Seperti orang Minang yang jago berdiplomasi di pasar, ia ambil ilmunya, tapi tidak ikut dijual prinsipnya.
Surau: Tempat Merenung dan Menajamkan Nurani
Di balik penampilannya yang rapi dan kecenderungan diam itu, Bung Hatta menyimpan satu akar yang sangat kuat: Islam dan surau Minangkabau. Jangan bayangkan surau sebagai tempat ibadah kaku. Di Sumatera Barat, surau adalah pusat kehidupan sosial dan spiritual. Anak laki-laki yang menginjak usia remaja, wajib “mondok” di surau. Di situlah ia belajar mengaji, adab, dan tanggung jawab sosial.
Hatta muda akrab dengan suasana itu. Ia bukan santri karbitan yang cuma hafal surat pendek. Ia benar-benar belajar agama dari gurunya langsung. Bahkan, di rumah, ia sering membaca tafsir dan buku keislaman sambil nyeruput teh atau menyendiri. Ini penting, karena kelak, nilai-nilai keislaman ini tidak ditinggalkannya ketika ia jadi aktivis dan negarawan.
Islam versi Bung Hatta bukan Islam tempelan. Bukan juga Islam “branding” buat narik massa. Tapi Islam yang tenang, dalam, dan sadar konteks. Dalam banyak tulisannya, Hatta sering menyebut keadilan sosial sebagai nilai yang diajarkan Islam. Bahkan, waktu ia mendalami ekonomi, ia menyaringnya lewat prinsip Islam: tidak boleh menindas, tidak boleh rakus, dan semua harus berbagi.
Itulah kenapa saat ia memikirkan sistem ekonomi pasca-merdeka, ia tidak memilih kapitalisme atau komunisme mentah-mentah. Ia memilih jalur koperasi. Jalur tengah. Jalur Islam.
Rotterdam: Dari Mahasiswa jadi Pemimpin Pergerakan
Tahun 1921, Bung Hatta melanjutkan studi ke negeri Belanda. Di sinilah “madrasah” ketiga dimulai. Tapi ini bukan madrasah dalam arti literal. Rotterdam memberinya pelajaran paling tajam dalam hidupnya: bahwa kemerdekaan bukan sekadar melepaskan diri dari penjajah, tapi membangun manusia merdeka.
Bung Hatta kuliah di Handels Hogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam. Tapi hidupnya tidak hanya di kampus. Ia juga aktif memimpin Perhimpunan Indonesia — organisasi pelajar Indonesia di Eropa yang makin hari makin radikal. Di sinilah ia menulis esai-esai tajam soal kolonialisme, nasionalisme, dan pentingnya kebebasan.
Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka), adalah semacam deklarasi intelektual: bahwa Indonesia tidak butuh reformasi kecil-kecilan dari Belanda, tapi kemerdekaan penuh dan harga diri. Tulisan ini bikin Belanda gerah. Ia sempat ditangkap dan diadili di Den Haag karena dianggap subversif. Tapi dia membela diri dengan pidato yang elegan dan cerdas — sampai juri pun diam tertegun.
Di Rotterdam, ia juga banyak membaca. Koleksi bukunya luar biasa. Marx dibaca, tapi juga Adam Smith. Tafsir Al-Qur’an ia pelajari, tapi juga buku Max Weber. Jangan heran kalau cara pikirnya sistematis, logis, tapi penuh empati. Ia tidak pernah membenci Barat, tapi juga tidak pernah memujanya membabi buta.
Di masa itulah Bung Hatta benar-benar tumbuh sebagai pemikir dunia ketiga yang punya akar Islam, pengalaman kolonial, dan wawasan global.
Tiga Madrasah, Satu Jiwa Merdeka
Kalau kita rekap, Bung Hatta tumbuh dari tiga ruang pendidikan yang kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Dari sekolah kolonial, ia belajar logika dan disiplin berpikir. Dari surau Minang, ia menyerap etika dan nilai-nilai Islam. Dari Rotterdam, ia mendapatkan keberanian untuk menyuarakan gagasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Tiga tempat ini membentuk Bung Hatta jadi manusia utuh: berilmu tanpa congkak, beragama tanpa menyakiti, dan berjuang tanpa pamrih. Sebuah kombinasi yang sekarang langka bukan main.
Bung Hatta bukan orang yang bikin gaduh. Ia tidak suka orasi berapi-api. Tapi pikirannya tajam. Ia tidak pernah ikut pesta politik, tapi ia tahu bagaimana membangun pondasi negara. Ia tidak pakai jargon-jargon agama, tapi hidupnya adalah tafsir nyata dari nilai-nilai tauhid, adil, dan amanah. Dalam dunia yang sekarang makin kacau, tulisan ini sebenarnya adalah ajakan: mari kita tengok kembali jejak Bung Hatta. Mari kita belajar dari ketiga madrasah itu — sekolah, surau, dan dunia.
Karena hari ini, kita butuh lebih banyak orang seperti Bung Hatta: yang punya ilmu tanpa arogan, iman tanpa fanatisme, dan keberanian tanpa kepentingan. Dan kalau tiga tempat itu berhasil membentuk satu Bung Hatta, mungkin kita bisa mulai membentuk generasi baru yang juga belajar dari sekolah, surau, dan dunia — dengan cara yang lebih jernih, lebih ikhlas, dan lebih penuh cinta pada negeri.


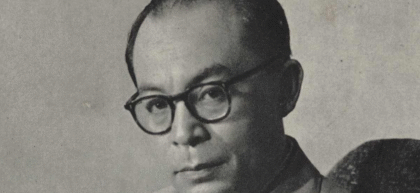
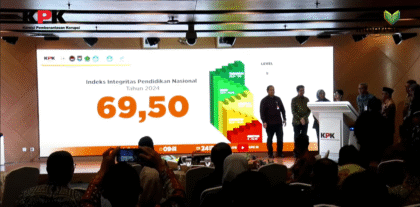
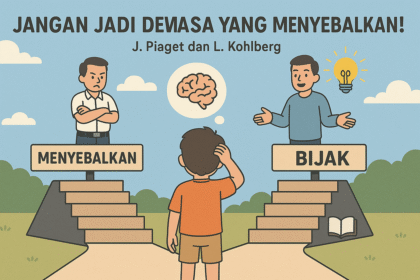




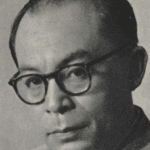


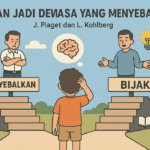
Komentar